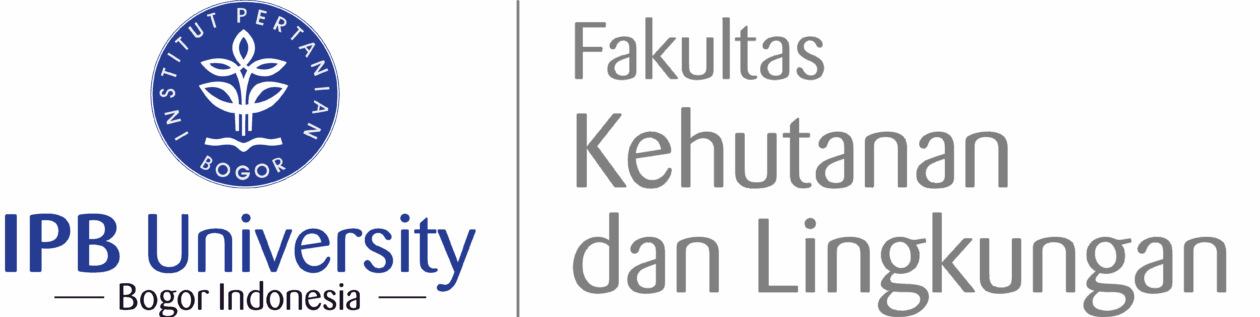Guru Besar Fahutan IPB University: Etnobotani di Papua Harus Jadi Dasar Pembangunan yang Berdaulat dan Berkelanjutan
Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan (Fahutan) IPB University, Prof Ervizal AM Zuhud menegaskan urgensi etnobotani dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berdaulat, terutama di Papua sebagai kawasan tropis.
Etnobotani adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan sumber daya tumbuhan lokalnya dalam pemanfaatan dan pengelolaannya secara berkelanjutan, turun temurun, kompak, dan spesifik lokal.
Menurut Prof Amzu, begitu ia kerap disapa, etnobotani merupakan pijakan utama dalam membangun kedaulatan bangsa, di setiap wilayah Indonesia berbasis sosio-budaya sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) spesifik lokal.
“Sepatutnya, hal itu juga disambungkan dan dikuatkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (ipteks) perguruan tinggi terkini yang tepat guna, dalam rangka mewujudkan di dunia nyata sila-sila Pancasila,” ujarnya.
Prof Amzu juga menekankan betapa mendesaknya perlindungan hutan alam, perawatan, pelestarian, dan pengembangan kearifan lokal dengan ipteks terkini perguruan tinggi.
Hal tersebut, kata dia, selama ini terabaikan akibat disorientasi arus modernisasi Barat dan perluasan aktivitas pertambangan yang tidak ramah lingkungan, mengejar semata income per kapita yang bersifat sangat jangka pendek dan sangat materialistik. Terlebih lagi, yang menikmati hasilnya hanya segelintir kelompok saja.
Padahal, masyarakat adat telah memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan secara turun-temurun untuk pangan, obat-obatan, pewarna, alat rumah tangga, bahkan racun.
“Pengetahuan ini, adalah aset bangsa yang perlu diangkat dan dikembangkan dengan ipteks terkini yang tepat guna sehingga terwujud nilai tambah tinggi dari SDA lokal kita di masing-masing wilayah NKRI. Hanya inilah yang bisa mewujudkan kedaulatan bangsa yang kuat secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Dalam konteks konservasi hutan tropis seperti di Raja Ampat, Papua Barat, Prof Amzu menyatakan bahwa praktik etnobotani suku Matbat di Pulau Misool, sangatlah menarik. Suku Matbat memiliki pengetahuan yang luas tentang tanaman dan tumbuhan yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti obat-obatan, makanan, dan upacara adat.
“Mereka memiliki sistem teknologi yang masih bersifat tradisional, seperti menggunakan alat-alat yang terbuat dari tumbuhan dan logam. Contohnya adalah penggunaan ‘noken’, tas yang terbuat dari anyaman bambu dan pelepah pohon sagu, dan atau serat tumbuhan lokal lainnya,” ulasnya.
Selain itu, suku Matbat juga memiliki praktik “sasi”, yaitu sistem pengelolaan SDA yang dilakukan dengan menutup pemanfaatan sumber daya dan wilayah dalam jangka waktu tertentu. Praktik ini, menurut Prof Amzu, sangat efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan SDA.
Meneliti praktik etnobotani suku Matbat, seperti hutan sagu, merupakan salah satu komponen penting dari keanekaragaman hayati di Pulau Misool. Sagu tidak hanya penting sebagai nilai ekonomi sumber pangan utama, tetapi juga secara ekologis, dan sosio-budaya mempunyai nilai yang tinggi dan strategis.
“Praktik etnobotani suku Matbat ini sangat penting dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional masyarakat adat di Papua Barat,” tandasnya.
Prof Amzu menilai bahwa eksploitasi hutan melalui ekspansi pertambangan di Papua akan membawa ancaman besar terhadap kelestarian hutan dan pengetahuan lokal masyarakat. Penambangan yang tidak memperhitungkan ekologi hanya akan mendatangkan kerugian jangka panjang, bahkan menjadi malapetaka yang sulit untuk dipulihkan.
Ia kemudian mengutip pernyataan seorang akademisi konservasi alam berkebangsaan Amerika, Aldo Leopold, yang menyatakan, ”Bila kehidupan alam semesta selama jutaan tahun telah membentuk suatu yang kita sukai, tetapi tidak kita pahami, lalu siapa lagi kalau bukan orang tolol dan bodoh yang malah mencopot bagian-bagian (merusak hutan) yang seakan-akan tidak ada gunanya.”
“Sagu itu bukan hanya makanan, tapi simbol kedaulatan dan kemandirian,” ucap dosen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (KSHE) IPB University ini. Ia juga menyampaikan bahwa hukum adat harus dijadikan landasan utama dalam pengembangan kebijakan pengelolaan tumbuhan tersebut.
“Hutan alam itu adalah perpustakaan hidup masyarakat lokal dan kita semua. Jika hutan hilang, kita kehilangan pengetahuan yang sangat berharga,” tegasnya.
Prof Amzu menyerukan kepada pemerintah agar memandatkan dan memerankan secara aktif semua perguruan tinggi di Indonesia dalam meneliti dan mengembangkan bioprospeksi tumbuhan lokal yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Pengetahuan lokal harus dikaji, disambungkan, dipadukan, dan dikuatkan dengan teknologi terkini yang tepat guna agar nilai tambahnya meningkat berlipat ganda, terutama bagi kesejahteraan masyarakat lokal secara lestari dan berkelanjutan,” katanya.
Menurutnya, pembangunan harus dilakukan secara terencana baik dengan pendekatan ekologi sebagai faktor penting dan utama. “Ekonomi bukan musuh ekologi. Justru ekonomi yang benar adalah yang tunduk pada prinsip-prinsip ekologi,” imbuhnya. Ia menambahkan bahwa keberlanjutan bukan hanya soal keuntungan jangka pendek, tetapi juga warisan yang akan ditinggalkan bagi generasi mendatang.
Prof Amzu juga mengkritik sistem otonomi daerah yang belum sepenuhnya berpihak pada potensi lokal. Ia menyarankan agar setiap wilayah di Indonesia diberdayakan berdasarkan keunikan SDA dan SDM lokalnya.
“Jadikan masyarakat lokal masing-masing wilayah Indonesia sebagai subjek pembangunan daerah mereka masing-masing,” tegasnya. Adapun langkahnya, Prof Amzu mengurai, libatkan mereka dalam perencanaan; tingkatkan kapasitas, kesadaran, dan pengetahuan melalui edukasi, pelatihan, pendampingan secara berkelanjutan.
Pemerintah, lanjut dia, juga harus menjamin akses masyarakat lokal ke SDA. Langkah terakhir, perlu mendorong dan melindungi pembangunan ekonomi lokal.
“Kalau perguruan tinggi diberi tanggung jawab dan peran sebagai ‘konco’ pembangunan masyarakat desa untuk mengembangkan sumber daya lokal berdasarkan undang-undang atau kebijakan pemerintah, maka setiap daerah bisa mandiri dan berdaulat dengan caranya sendiri,” tuturnya.
Sebagai penutup, ia menandaskan, “Perguruan tinggi tidak sebagai menara gading atau tidak hanya puas dengan publikasi penelitian yang terindeks Scopus.” (dr)